Kehidupan saban hari memberi ruang dan peluang untuk kita belajar sesuatu daripadanya. Mungkin kita lihat ia sebagai satu ketika yang hanya rawak atau satu saat yang hanya kebetulan. Namun, tiada apa yang ditakdirkan Tuhan berlaku ibarat angin bertiup lalu, melainkan membawa bersamanya sesuatu untuk direnung dan difikirkan. Sesuatu yang dapat dijadikan pedoman dalam mendepani ragam dan rencam kehidupan. Banyak kisah kehidupan yang membekas kuat dalam hati dan fikiran, yang membentuk kita menjadi manusia yang lebih peduli dan empati.
Benarkan aku memetik tulisan Brené Brown dalam bukunya Rising Strong: How the Ability to Reset Transforms the Way We Live, Love, Parent, and Lead dalam memberi definisi pada apa yang dikatakan sebagai empati.
Empathy: The most powerful tool of compassion, empathy is an emotional skill that allows us to respond to others in a meaningful, caring way. Empathy is the ability to understand what someone is experiencing and to reflect back that understanding. It’s important to note here that empathy is understanding what someone is feeling, not feeling it for them.

Peristiwa yang tidak dirancang.
Manusia yang kita jumpa.
Perbualan yang berlaku.
Kata-kata yang disebut.
Entah berapa kali aku berada dalam situasi yang sangat memberi kesan, yang mendidik aku supaya tidak gopoh menghakimi dan berusaha dahulu untuk memahami. Entah berapa kali juga aku berada dalam situasi yang mengajar aku mengawal emosi, yang menyedarkan aku bahawa manusia punya banyak sebab dan musabab yang perlu diperhalusi. Kehidupan ini tidak beroperasi in silos, banyak pemboleh ubah yang perlu dihitung. Di sinilah acap kali kaki tersadung pada kedangkalan akal dalam menimbang betapa kompleksnya dunia, kehidupan, dan manusia.
Peribahasa Inggeris ada menyebut, “Before you judge a man, walk a mile in his shoes.”
Aku bersetuju dengan kata-kata tersebut.
Namun, bukan mudah untuk berjalan dengan memakai kasut manusia lain. Awal-awal lagi saiz kaki mungkin sudah tidak sama, fesyen kasut yang tidak cocok dengan gaya sendiri, dan rasa tidak selesa memakai kasut bekas kaki manusia lain. Itu hanya perumpamaan.
Aku sedar, ada banyak situasi yang aku tidak berusaha untuk memahami. Ia mungkin berlaku atas faktor masa, tiada sumber untuk mendapatkan maklumat tambahan, atau bukan keutamaan aku ketika itu untuk memahami situasi tersebut.
Oleh sebab aku sendiri tidak berusaha untuk memahami, aku tidak wajar untuk menghakimi. Bahkan, aku sebenarnya tidak akan sama sekali berada pada posisi yang melayakkan diri untuk menghakimi. Siapa aku? Dalam situasi sedemikian, lebih moleklah jika aku bersangka baik sahaja, mengandaikan yang pasti ada keuzuran daripada manusia terbabit yang menyebabkan situasi tersebut menjadi sedemikian rupa. Biarlah aku berpada dengan alasan yang aku sendiri ciptakan dan teruskan sahaja kehidupan dengan jiwa yang lebih tenang.
…
Petang itu, kami bertiga keluar untuk cari makan malam. Aku sendiri sudah lapar. Kami memilih sebuah restoran yang belum pernah kami cuba. Seperti biasa, Ayah yang akan turun pesan, aku dan Mama hanya menunggu di dalam kereta. Kami melihat sahaja suasana di restoran itu. Hampir sejam kami menunggu sebelum pesanan kami siap, walhal tiada pelanggan lain ketika itu. Harga makanan yang dibayar mahal. Nasi goreng Pattaya yang dipesan, nasi goreng Padprik yang aku dapat. Tiada guna lagi, makanan sudah dibawa pulang ke rumah. Aku makan hanya sedikit, tanda rasa tidak puas hati dengan apa yang berlaku. Ketika itulah Mama berkata, “Sekarang baru kita tahu betapa susah orang nak kerja untuk hidup.”
Zahirnya, apa yang disebut Mama seperti tiada kaitan dengan apa yang berlaku. Itu pun jika dipandang dengan mata kasar. Yang aku lihat ketika itu hanyalah ruang yang sangat luas untuk mengeluh dan berasa tidak puas hati dengan servis yang diberi. Tetapi, pernahkah aku cuba dahulu untuk memahami apa yang berlaku kepadanya pada hari itu?
Kami membuat andaian. Mungkin dia kekurangan pekerja. Boleh jadi pekerjanya terpaksa mengambil cuti kecemasan. Namun, dia tetap perlu membuka restoran supaya dirinya sendiri memperoleh sedikit pendapatan untuk hari tersebut. Maka, dia seorang sahajalah yang membuat segala-galanya. Ambil pesanan, masak, dan jadi juruwang. Pinggan mangkuk di atas meja pelanggan sebelum kami sampai pun masih di situ, belum sempat dikemas. Apa boleh buat, dia tetap perlu melakukan yang terbaik dalam keadaan yang kurang serba-serbi.
Aku tidak dapat makan nasi goreng Pattaya pada malam itu, tetapi aku dapat satu kesedaran bahawasanya dunia ini tidak berputar mengelilingi aku semata-mata. Aku hanya tidak mendapat kemahuan aku, tetapi dia pula mungkin sedang berhempas-pulas memenuhi keperluan dirinya.
…
Tamat sahaja kelas, rakan aku yang juga pengasas NGO yang menggerakkan projek kelas tuisyen percuma tersebut mengajak aku berbincang. Ada perkara yang dia tidak puas hati dan aku mengerti sebabnya. Perihal seorang sukarelawan yang sering datang lewat dan pernah tidak hadir tanpa kemukakan sebab. Aku sendiri baru sahaja lepas rasa marah dengan keluarga murid yang aku anggap sambil lewa dalam menitikberatkan soal ketepatan waktu dan juga pernah tidak hadir tanpa kemukakan sebab. Kesabaran aku untuk menunggu semakin menipis, apatah lagi menunggu seseorang yang belum pasti kehadirannya.
Di celah-celah ketidaksabaran aku itu, acap kali aku ingatkan diri, bahawa ada sebab ia terjadi sebegitu. Bagi aku, kemampuan seseorang untuk menepati waktu dibantu oleh sistem yang menyokong dalam kehidupannya. Aku bersyukur kehidupan aku punya sistem yang membuatkan aku tidak perlu serabut berfikir soal makan pakai seharian. Soal asas sebegini, sayangnya, menjadi punca keserabutan kehidupan sebahagian manusia. Sistem yang menyokong belum tentu wujud dalam kehidupan manusia lain. Acap kali juga aku ingatkan diri, bahawa aku tidak mengetahui sepenuhnya kehidupan murid itu, juga sukarelawan yang dimaksudkan. Apa yang mereka lalui dalam seharian? Apa cabaran yang mereka hadapi? Adakah mereka punya sistem sokongan yang diperlukan?
Boleh sahaja aku mudah-mudah mengatakan yang ini semua soal sikap, soal tidak meletakkan nilai menghargai masa pada kedudukan yang tinggi. Ya, mungkin itulah puncanya. Tetapi sebolehnya aku tidak mahu sampai ke situ untuk menghakimi sukarelawan dan keluarga murid itu. Isu yang berlaku tetap perlu diberitahu, tidak wajar kita selama-lamanya berfikir kelewatan itu diterima. Tetapi tidaklah pula sehingga terlajak menghukum tanpa bertanya dahulu apa sebab ia terjadi sebegitu. Seek first to understand… begitulah pesan Stephen Covey.
…
Sudah beberapa hari aku cuba menghubungi seorang ibu anak tujuh, tetapi tidak berjaya. Dia langsung tidak membalas mesej atau cuba untuk menghubungi aku semula. Aku masih tidak diberi sebab kenapa anaknya yang keenam itu tidak hadir ke kelas minggu sebelumnya. Cepat betul ketika itu aku beranggapan yang dia acuh tidak acuh sahaja untuk menghantar anaknya ke kelas. Maklumlah, kelas percuma yang mungkin dipandang ringan sahaja oleh sebahagian manusia.
Pada satu hari, dia menghantar anaknya itu ke kelas yang kami adakan di sebuah masjid pada setiap minggu. Sempat kami berbual. Rupa-rupanya, anak bongsunya dimasukkan ke wad ICU di hospital. Sakit teruk, doktor sendiri memberitahu peluang hanya 50-50 ketika itu. Penyakit yang dia sendiri tidak reti untuk menyebutnya dengan betul. Syukur, dipanjangkan umur dan dapat pulang ke rumah yang belum sempurna keadaannya. Persekitaran rumah yang tidak sesuai menyulitkan lagi proses penyembuhan. Dia nekad perlu berpindah sementara menunggu rumahnya itu siap lebih elok.
Aku kenal keluarga murid itu lebih daripada sebahagian murid yang lain. Banyak kisah yang diceritakan, baik daripada murid sendiri atau ibunya. Bukan mudah menjadi ibu tunggal yang membesarkan lima orang lagi anak yang masih lagi bawah tanggungjawabnya. Tanpa sistem sokongan yang utuh, sesiapa pun mudah tersungkur jatuh. Tidak menang tangan dia melakukan segala-galanya. Soal persekolahan anak-anak terus terabai. Anaknya yang keenam itu tidak pernah bersekolah kerana tidak punya dokumen. “Hari-hari cik nak pi sekolah”, terngiang-ngiang suara murid aku memberitahu kemahuannya ketika kelas.
Pernah ibunya menghantar mesej kekecewaannya kepada aku setelah urusan dokumen anaknya masih tidak dapat diuruskan. Dihantar juga gambar murid aku yang sedang makan roti di luar bangunan kerajaan, mungkin setelah keletihan berurusan di jabatan yang penuh birokrasi. Aku sendiri tidak tahu mahu membalas apa. Entah kenapa dibuat sungguh payah untuk seorang kanak-kanak dapat bersekolah.
Kiri kanan mereka berjirankan manusia yang mudah sahaja menghakimi tanpa cuba dahulu untuk memahami. Ada sahaja fitnah yang dilemparkan. Dipanjangkan pula fitnah itu kepada tuan punya rumah. Beralasankan tunggakan sewa rumah berjumlah RM200 yang belum dibayar, mereka disuruh keluar. Sepanjang tempoh beberapa bulan kelas aku dengan murid itu, sudah beberapa kali mereka berpindah-randah. Pada ketika aku beranggapan yang mereka acuh tidak acuh sahaja dengan kelas kami, rupa-rupanya mereka sendiri sedang bergelut dengan kehidupan.
Kehidupan mereka rapuh. Masih tergamakkah aku menganggap yang mereka acuh tidak acuh?
…
Tipulah jika tidak pernah terlintas dalam fikiran bahawa hanya aku sahaja yang cuba untuk memahami manusia lain, adakah manusia lain juga cuba untuk memahami aku? Kadang-kadang, tanpa sedar aku sendiri menafikan keupayaan empati itu ada pada manusia lain. Aku teringat apa yang pernah disebut oleh kaunselorku saat aku sendiri merasakan sangat sukar untuk meminta bantuan. Katanya, “Awak kena ingat yang mereka juga punya empati. Mereka juga akan cuba untuk faham apa yang awak hadapi. Awak perlu beri ruang untuk mereka bantu awak.”
…then to be understood, begitulah sambungan pesan Stephen Covey.
Mengapa aku menulis semua ini?
Barangkali kerana aku mengenang pada apa yang pernah ditulis oleh HAMKA dalam Dari Lembah Cita-Cita. Katanya, “Jangan dibiarkan segala perkara yang berlalu di hadapanmu dengan begitu sahaja tetapi pertalikanlah dengan dirimu, kerana segenap alam ini bertali senantiasa dengan manusia.”
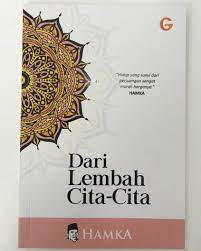
Barangkali juga kerana aku mengingati apa yang disebut oleh James Pennebaker seperti yang dipetik oleh Brené Brown dalam bukunya tadi. Katanya, “Emotional upheavals touch every part of our lives… Writing helps us focus and organize the experience.” Segala perkara yang berlaku membentuk pengalaman yang berantakan. Maka akal kita akan cuba untuk mengatur dan menterjemah pengalaman tersebut ke dalam bentuk bahasa yang bisa difahami melalui penulisan, pada kadar yang direzekikan Tuhan untuk difahami.
Kita tidak akan pernah sempurna dalam memahami. Banyak waktu, akan ada ruang ia dikaburi dengan pemahaman sendiri yang jauh menyimpang daripada realiti. Pemahaman sendiri tentang dunia, kehidupan, dan manusia tentulah terhad dan dipengaruhi oleh apa yang diketahui kita sahaja. Kadangkala, pemahaman sendiri itu sangat naif. Sedangkan dunia, kehidupan, dan manusia itu sifatnya kompleks, dan kekal kompleks sehingga hujung waktu.
Tiada jalan mudah dalam usaha untuk memahami melainkan perlu meletakkan pemahaman sendiri ke tepi sebentar dan cuba lihat dari sudut pandang manusia lain dahulu. Dengar cerita mereka. Fahami konteks mereka. Hidup dengan mereka. Ia bukan kerja mudah kerana masing-masing punya kehidupan sendiri yang perlu dijalani. Tidak ada celah dalam kehidupan kita untuk menjalani kehidupan manusia lain. Di situlah kelemahan yang harus kita akui. Itulah sebab kita tidak akan pernah sempurna dalam memahami. Masih wajarkah kita menghakimi?
Cukup mudah kita kata padanya begini begitu.
Pernahkah kita berjalan memakai kasutnya sejauh sebatu?
Disediakan oleh,
Syamim Binti Hashim
